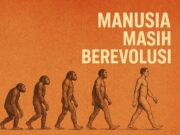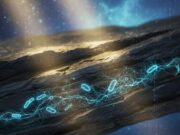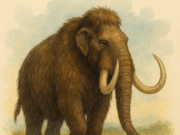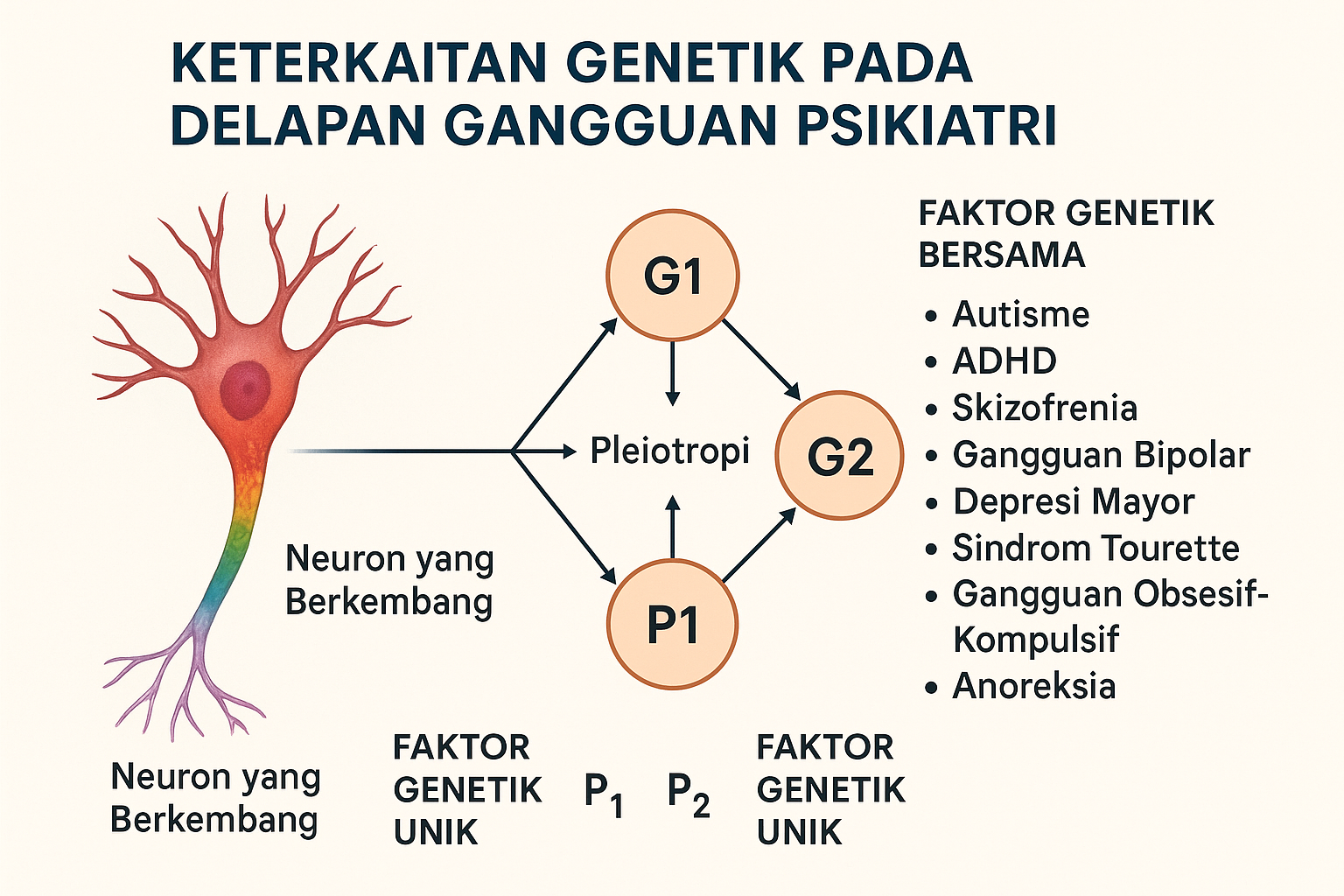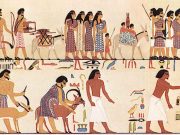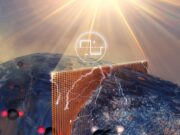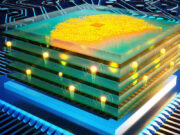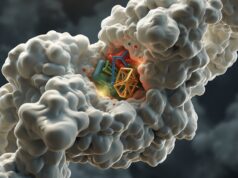Gambut merupakan bentuk ekosistem vegetasi yang terbentuk akibat pelapukan bahan organik dalam kondisi lingkungan yang kekurangan oksigen (anaerob), biasanya karena tergenang air. Lingkungan seperti ini berperan sebagai “lemari pendingin alami” yang mampu mengawetkan sisa-sisa tumbuhan seperti biji dan benang sari, yang menjadi objek penting dalam studi paleoekologi. Vegetasi gambut biasanya berkembang di wilayah cekungan yang terletak di belakang daerah rawa.
Terdapat dua jenis gambut utama, yaitu ombrogen dan topogen. Gambut ombrogen terbentuk di daerah cekungan dalam dengan kedalaman bisa mencapai 20 meter. Jenis ini miskin unsur hara, terutama kalsium, serta memiliki air dengan tingkat keasaman yang tinggi. Tanaman tumbuh di atas tumpukan serasah organik dari vegetasi sebelumnya, tanpa pasokan mineral dari luar, dan proses pembentukannya sangat dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi.
Sebaliknya, gambut topogen memiliki kondisi yang relatif lebih subur, dengan kedalaman kurang dari 4 meter. Airnya masih agak masam, namun lebih kaya hara karena adanya siklus naik-turun air yang menyebabkan proses oksidasi serasah pohon dan pembentukan mineral. Beberapa tumbuhan yang umum ditemukan di wilayah ini antara lain ramin (Gonystylus bancanus) dan palawan (Tristania sp.).
Hutan gambut ditandai oleh lapisan bahan organik tebal (lebih dari 1 meter), sedangkan hutan rawa yang mengandung gambut berada di zona transisi yang memperlihatkan kombinasi elemen gambut dan rawa. Vegetasi di hutan bergambut menunjukkan variasi tinggi tajuk pohon dan bersifat campuran, namun tetap memiliki keanekaragaman spesies yang lebih rendah dibandingkan hutan hujan tropis pohon dikotil. Ketinggian pohon bisa mencapai 30 meter di bagian pinggiran, namun akan semakin pendek ke arah pusat, seiring kondisi lingkungan yang semakin ekstrem.
Vegetasi di bagian pusat gambut, terutama saat lapisan gambut lebih dari 2 meter, sering kali berupa hutan cebol (dwarf forest atau Krüppelhölz). Flora hutan gambut meliputi berbagai jenis, mulai dari gulma hingga spesies khas seperti Pandanus, Podocarpus, serta keluarga Dipterocarpaceae. Banyak tumbuhan di ekosistem ini bersifat khas, namun jumlah total spesiesnya cenderung terbatas karena kondisi tanah yang sangat asam (pH sekitar 3,2). Misalnya, di Sumatra hanya ditemukan sekitar 100 spesies pohon di hutan gambut.
Hutan gambut sering kali didominasi oleh satu atau dua spesies saja dan membentuk tegakan hampir murni di area luas, seperti Gonystylus bancanus dan G. macrophyllus di Kalimantan Barat, serta Campnosperma macrophylla di Sumatra. Komposisi vegetasi berubah secara bertahap dari pinggiran ke pusat gambut, mengikuti ketebalan lapisan organik. Di beberapa wilayah Sumatra, zona-zona vegetasi dari tepi ke pusat mencakup:
- Hutan dengan tumbuhan bawah yang rapat, terutama palem seperti Licuala, Zallaca, dan beberapa jenis rotan.
- Hutan lebat.
- Hutan tinggi (high forest) dengan campuran pohon kecil dan cebol.
- Hutan cebol yang didominasi oleh Tristania, terutama Tristania obovata dan Pleiarium alternifolium, serta adanya liana seperti Nepenthes ampullaria.
Komposisi tumbuhan di hutan gambut sangat bergantung pada karakteristik kimia tanah gambut. Variasi dominasi spesies mencerminkan perbedaan kondisi tersebut. Beberapa spesies yang disebutkan mencakup:
Autidesma puncticulatum, Artocarpus elasticus, Alstonia pneumatophora, Baccaurea bracteata, Calophyllum spectabile, Dillenia excelsa, Durio carinatus, Pithecelebium clypearia, Polyalthia laterifolia, Elaeocarpus sphaericatus, Ficus variegata, Gymnacranthera eugeniafolia, Knema conferta, Koompassia excelsa, Macaranga macrophylla, Hopea sagal, Uncaria gambir, Zallaca conferta, dan Shorea acuminata.
Jika ekosistem gambut dikeringkan, hutan gambut bisa berubah menjadi daerah yang didominasi paku-pakuan seperti Gleichenia sp. Spesies asli pun akan hilang. Hal serupa terjadi di daerah pasang surut yang terganggu karena penggalian, yang menyebabkan air gambut terperangkap dan tidak bisa mengalir keluar. Hal ini memicu penurunan pH dan mengakibatkan tanah kehilangan gambutnya.
Air merupakan faktor paling berpengaruh dalam menentukan jenis tumbuhan yang bisa hidup di hutan gambut. Macaranga sp. dan Mallotus sp. biasanya muncul sebagai pionir pasca kebakaran. Bila kebakaran terjadi berulang kali tanpa pencegahan, maka Melastoma sp. (senduduk) akan berkembang, karena memiliki toleransi tinggi terhadap kondisi gambut yang rusak — membentuk fase piriklimaks.
📝 Latihan Soal Pilihan Ganda: Ekologi Hutan Gambut Tropis
Results
#1. Karakteristik utama tanah gambut yang memengaruhi pertumbuhan vegetasi adalah …
#2. Salah satu faktor pembatas utama bagi tumbuhan di hutan gambut adalah …
#3. Jenis pohon yang umum ditemukan di lapisan atas (kanopi) hutan gambut adalah …
#4. Salah satu adaptasi tumbuhan hutan gambut terhadap kondisi anaerob adalah …
#5. Peran penting hutan gambut dalam ekosistem hutan tropis adalah …
#6. Vegetasi di hutan gambut cenderung menunjukkan tingkat endemisitas tinggi karena …
#7. Ekosistem hutan gambut diklasifikasikan sebagai sub-ekosistem hutan tropis karena …
#8. Salah satu dampak negatif dari pengeringan hutan gambut adalah …
#9. Tumbuhan bawah seperti Nepenthes spp. (kantong semar) sering ditemukan di hutan gambut karena …
🧾 Daftar Referensi Ilmiah Pendukung
- Priatna, D., et al. (2021).
Strategi dan Teknik Restorasi Ekosistem Hutan Rawa Gambut
Menjelaskan klasifikasi gambut ombrogen dan topogen, peran vegetasi khas seperti Gonystylus bancanus dan Tristania sp., serta pentingnya air sebagai pengendali struktur dan fungsi ekosistem.
📄 PDF – ResearchGate - Sukmana, A., et al. (2023).
Bunga Rampai Kelestarian dan Konservasi Hutan Rawa Gambut di Indonesia
Memberikan penjelasan rinci tentang landform gambut topogen (G1) dan ombrogen (G2), serta komposisi vegetasi berdasarkan kedalaman dan keasaman gambut.
📄 PDF – ResearchGate - Maftuah, E., & Nurzakiah, S. (2017).
Pemulihan dan Konservasi Lahan Gambut
Menjelaskan struktur ekologis gambut ombrogen dan topogen, peran hujan dalam pembentukan, serta dominasi spesies khas pada kondisi pH rendah.
📄 PDF – ResearchGate - Sukarna, R., et al. (2016).
Kajian Bentang Lahan Ekologi Floristik Hutan Rawa Gambut di Sebangau
Menggunakan penginderaan jauh untuk memetakan perubahan vegetasi gambut serta keterkaitan topografi dengan distribusi spesies.
📄 PDF – ResearchGate - Narendra, B.H., et al. (2023).
Peran Hidrologi Hutan Rawa Gambut dan Dampak Degradasinya
Menjelaskan perubahan struktur vegetasi akibat gangguan air, dan hilangnya spesies asli setelah degradasi atau pengeringan gambut.
📄 PDF – ResearchGate - Lestari, K.G. (2022).
Faktor yang Mempengaruhi Suksesi di Lahan Bekas Terbakar
Memberikan analisis tentang vegetasi pionir pasca-kebakaran seperti Macaranga sp. dan Melastoma sp., serta perubahan piriklimaks akibat kebakaran berulang.
📄 PDF – ResearchGate - Yulianto, E., et al. (2019).
Palynostratigraphy, Paleoecology and Paleoclimatology of Early Pleistocene
Menguatkan pernyataan tentang kemampuan lapisan gambut mengawetkan serbuk sari dan biji, sebagai bahan studi paleoekologi.
📄 PDF – ResearchGate - Peta, M.S., et al. (2021).
Restorasi Ekosistem Hutan Rawa Air Payau Tipe Marine Clay
Mendukung informasi tentang spesies khas hutan rawa gambut seperti Gonystylus bancanus, serta efek pH tanah terhadap dominasi jenis.
📄 PDF – ResearchGate