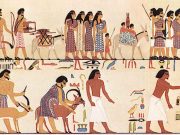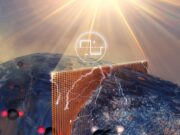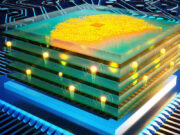“Hari itu, saya pulang ke rumah dan menangis,” kata Benny Lam saat mengisahkan pengalaman memotret kehidupan suram di Hongkong. Setelah empat tahun mengunjungi lebih dari 100 rumah susun di distrik tua kota tersebut, Lam terbiasa dengan rumah berlantai kayu seluas 4 meter persegi yang dikenal sebagai “bilik peti mati”.
Saat ia memotret bilik yang sedikit lebih besar dari biasanya, Lam berseru pada penyewanya, “Anda punya rumah peti mati yang besar!”
“Saya merasa sedih,” kenang Lam, “Hidup seperti itu seharusnya tidak pernah dianggap normal. Saya sudah mati rasa.”
 Hongkong penuh dengan jajaran pertokoan dengan lampu neon terang yang menjual barang-barang bermerk mewah, perhiasan dan perangkat teknologi untuk menyenangkan konsumen. Cakrawala yang dipenuhi gedung-gedung pencakar langit berisi beragam bisnis membuat Hongkong menjadi salah satu pusat keuangan utama dunia.
Hongkong penuh dengan jajaran pertokoan dengan lampu neon terang yang menjual barang-barang bermerk mewah, perhiasan dan perangkat teknologi untuk menyenangkan konsumen. Cakrawala yang dipenuhi gedung-gedung pencakar langit berisi beragam bisnis membuat Hongkong menjadi salah satu pusat keuangan utama dunia.
Namun di balik kehidupan kota yang glamor, sekitar 200.000 orang, termasuk 40.000 anak-anak, tinggal di tempat yang ukurannya berkisar antara 4 hingga 30 meter persegi.
Dengan populasi hampir mencapai 7,5 juta penduduk dan hampir tak ada lagi lahan kosong tersisa, pasar perumahan Hongkong meningkat menjadi yang paling mahal di dunia.
 Terdesak oleh harga sewa yang melonjak, puluhan ribu orang tak punya pilihan selain menghuni gubuk liar; rumah susun yang terbagi-bagi dengan dapur dan toilet menyatu; bilik seukuran peti mati; dan rumah kandang yang terbuat dari jalinan kawat.
Terdesak oleh harga sewa yang melonjak, puluhan ribu orang tak punya pilihan selain menghuni gubuk liar; rumah susun yang terbagi-bagi dengan dapur dan toilet menyatu; bilik seukuran peti mati; dan rumah kandang yang terbuat dari jalinan kawat.
 “Dari memasak hingga tidur, semua aktivitas dilakukan di ruang sempit ini,” kata Lam.
“Dari memasak hingga tidur, semua aktivitas dilakukan di ruang sempit ini,” kata Lam.
Untuk membuat bilik peti mati, rumah susun seluas 120 meter akan disekat secara ilegal oleh pemiliknya guna menampung 20 ranjang susun. Masing-masing ranjang disewakan dengan harga 200 dolar Hongkong (sekitar 25 dolar AS) per bulan. Bilik ini bahkan tidak akan muat jika seseorang berdiri di dalamnya.
 Dalam serial fotonya yang berjudul “Trapped”, Lam ingin ‘menerangi’ tempat tinggal nan mencekik yang tak terjangkau oleh cahaya kesejahteraan Hongkong. Ia berharap, dengan membuat para penyewa dan rumah sempit mereka terlihat, akan lebih banyak orang yang memberi perhatian terhadap ketidakadilan sosial yang mereka alami.
Dalam serial fotonya yang berjudul “Trapped”, Lam ingin ‘menerangi’ tempat tinggal nan mencekik yang tak terjangkau oleh cahaya kesejahteraan Hongkong. Ia berharap, dengan membuat para penyewa dan rumah sempit mereka terlihat, akan lebih banyak orang yang memberi perhatian terhadap ketidakadilan sosial yang mereka alami.
“Anda mungkin bertanya-tanya mengapa kita harus peduli, padahal orang-orang ini bukan bagian dari hidup kita,” tulis Lam di laman Facebooknya.
 “Merekalah orang-orang yang datang ke kehidupan Anda setiap hari: mereka melayani Anda sebagai pelayan di restauran tempat Anda makan, mereka adalah petugas keamanan yang menjaga pusat perbelanjaan tempat Anda berjalan-jalan, atau petugas kebersihan di sana dan para kurir di jalan yang tiap hari Anda lewati. Perbedaan di antara kita dan mereka hanyalah rumahnya. Ini adalah sebuah masalah tentang martabat manusia.”
“Merekalah orang-orang yang datang ke kehidupan Anda setiap hari: mereka melayani Anda sebagai pelayan di restauran tempat Anda makan, mereka adalah petugas keamanan yang menjaga pusat perbelanjaan tempat Anda berjalan-jalan, atau petugas kebersihan di sana dan para kurir di jalan yang tiap hari Anda lewati. Perbedaan di antara kita dan mereka hanyalah rumahnya. Ini adalah sebuah masalah tentang martabat manusia.”
Lam menemukan sebuah foto yang memilukan. Dalam foto itu, seorang pria berbaring di ranjangnya. Pria itu bahkan tak dapat menyelenjorkan kaki sepenuhnya, dan bagian lututnya menyentuh dinding bilik peti mati. Ia makan kacang panggang dari kaleng—mungkin makan malam, dan menonton TV kecil yang menampilkan gambar pelangi. Binatu bergelantungan dari langit-langit yang rendah.
 Bagi Lam, itu adalah contoh klasik untuk menunjukkan pada lebih banyak penduduk yang berkecukupan dan pemerintah, mengapa mereka harus bertindak untuk mengatasi krisis perumahan dan kesetaraan pendapatan di Hongkong.
Bagi Lam, itu adalah contoh klasik untuk menunjukkan pada lebih banyak penduduk yang berkecukupan dan pemerintah, mengapa mereka harus bertindak untuk mengatasi krisis perumahan dan kesetaraan pendapatan di Hongkong.
Keteguhan hati para laki-laki, perempuan, dan keluarga yang membuka pintu rumah serta berbagi cerita mereka dengan orang asing, melekat kuat dalam benak Lam. Sebagian besar dari mereka merasa malu tinggal di ruang sempit semacam itu, kata Lam. Tetapi mereka berharap saat orang-orang melihat foto-foto ini, mereka akan mendapatkan bantuan dan dukungan.