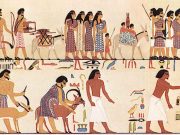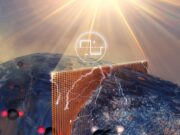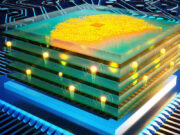Kolonel Samuel Marshall adalah seorang jurnalis dan sejarawan militer yang menulis sebuah buku Men Against Fire yang diterbitkan di tahun 1946. Apa yang paling mengejutkan dari temuannya selama peperangan yang ia ikuti, bahwa sebagian besar serdadu tidak menembakkan senjatanya. Sesuatu yang mungkin bisa mengubah bayangan seseorang tentang perang yang cenderung lebih banyak disaksikan melalui novel dan layar lebar.
Di tahun 1943, Marshall mendampingi kontingen pertama Amerika yang mendarat untuk mencoba merebut sebuah pulau di Pasisfik dari tangan Jepang. Pasukan hanya mampu bergerak sejauh lima kilometer di hari pertama dan tidak menyadari ada kamp Jepang yang tak jauh dari mereka. Saat malam tiba, Jepang menyerbu posisi Amerika, sebelas kali. Meski kalah jumlah, mereka hampir berhasil menerobos garis Amerika.
Sebagai seorang ahli sejarah, pertempuran ini ibarat sebuah lab yang dapat Marshall amati secara langsung. Ia kemudian bertanya-tanya karena merasakan suatu kejanggalan. Dia lalu mengumpulkan para serdadu dan mewancarainya. Semua orang dimintanya untuk berbicara secara bebas dan terbuka. Bagi yang berpangkat lebih rendah, boleh saja tidak sepakat dengan atasannya.
Senjata yang tak terpakai
Dalam hal strategi peperangan, apa yang telah direncanakan pasukan AS bisa dianggap jenius. Namun Marshall akhirnya menemukan rahasia peliputan pertempuran secara akurat. Sesuatu yang kemudian akan menjadi kontroversi dan pertentangan. Ternyata, sebagian besar prajurit tak pernah menembakkan senjatanya.
Berdasarkan wawancaranya terhadap kelompok-kelompok prajurit, di Pasifik dan kemudian di Eropa, ditemukan bahwa hanya 15 sampai 25 persen yang benar-benar menembakkan senjata. Pada saat pertempuran malam di pulau Pasifik, Marshall menemukan bahwa sebuah batalion yang beranggotakan tiga ratus lebih seradadu, hanya tiga puluh enam orang saja yang benar-benar menarik pelatuk senjatanya.
Banyak yang menentang apa yang telah ditemukan Marshall tersebut, bahkan hingga beberapa dekade setelah bukunya diterbitkan. Tapi, ia tidak sedirian. Dalam sebuah pertempuran di tahun 1944, diceritakan bagaimana seorang perwira begitu frustasi dan berteriak-teriak kepada barisan serdadunya: “God damn it! Start shooting!”. Tapi itu tidak banyak membantu. Mereka menembak hanya ketika mereka merasa diawasi atasannya, keluh perwira tersebut.
Para kolega Marshall di garis depan mengamati hal yang serupa. Dalam aksi militer tahun 1943 di Sisilia, seorang letnan mengeluh bahwa dia tak bisa mengandalkan lebih daripada seperempat pasukannya. Seorang jenderal menulis dalam sebuah suratnya mengatakan bagaimana para pemuda Britania tidak punya sifat dasar sebagai pembunuh.
Para ahli sejarah kemudian turut mewancarai para veteran perang, dan didapati bahwa lebih dari setengahnya tak pernah membunuh siapa pun. Di Angkatan Udara AS, tak sampai 1 persen pesawat musuh yang dijatuhkan. Sebagian besar pilot tak pernah menembak jatuh siapa pun, atau bahkan mencoba untuk melakukannya.
Menelusuri kebenaran
Temuan-temuan itu semakin mendorong para ahli untuk menelusurinya lebih jauh hingga Perang Saudara 1863. Pemeriksaan dari sekitar 27.000 lebih bedil yang dikumpulkan kembali dari medan laga mengungkapkan bahwa 90 persennya masih terisi peluru. Ini sulit dipercaya.
Dalam sebuah pertempuran di 1860-an, serdadu Prancis juga sama-sama tidak suka bertempur menurut sebuah temuan. Ketika menembakkan senjata, mereka sering membidik terlalu tinggi. Padahal, perlu waktu lama untuk mengisi peluru, lalu ditembakkannya di atas kepala musuh.
Sejumlah pakar akhirnya mendukung kesimpulan-kesimpulan Kolonel Marshall. Randall Collins yang menganalisis ratusan foto serdadu yang bertempur nengidentifikasi bahwa hanya 13 sampai 18 persen dari serdadau yang menembakkan senjatanya.
Dalam sebuah pertempuran, para serdadu tentu ada yang mengalami kematian. Tapi pemeriksaan forensik korban dari kematian serdadu Bitania pada Perang Dunia II, menemukan bahwa 75% kematian disebabkan oleh mortir, granat, bom dari udara dan peluru meriam. Kematian akibat peluru, dan ranjau antitank sebesar 10%.
Sebagian besar serdadu tewas karena seseorang menekan tombol, menjatuhkan bom, atau memasang ranjau. Itu dilakukan oleh seseorang yang tak pernah melihat mereka, memandang wajah atau bertatap mata. Pembunuhan dilakukan dari jarak jauh, seiring perkembangan teknologi militer.
Bisa saja para serdadu diberi obat yang menumpulkan empati dan antipati alami terhadap kekerasan. Atau seperti yang disarankan Kolonel Marshall kepada angkatan darat AS, saat menghadapi Vietnam. Orang-orang yang berhasil direkrut dalam perang, bukan hanya dibina rasa persaudaraan tapi juga kekerasan brutal, memaksa mereka berteriak “BUNUH! BUNUH! BUNUH!” sampai suara serak. Pengkondisian dengan cara ini dianggap ampuh.
Jika manusia baik, mengapa bisa kejam?
Semua uraian di atas mengantarkan kita pada suatu pertanyaan besar. Mungkin saja jawabannya adalah gambaran tentang manusia yang paling mendasar. Manusia pada dasarnya makhluk yang baik, bukan makhluk buas yang diselimuti sebuah lapisan tipis peradaban atau makhluk yang terlahir egois. Manusia mungkin takut menarik pelatuk senjatanya karena tak tega. Tapi, ia juga bisa melumatkan sesamanya secara brutal tanpa belas kasihan.
Brian Hare, seorang profesor antropologi evolusi mengatakan, bahwa mekanisme yang membuat manusia spesies paling baik hati, juga membuatnya sebagai spesies paling sadis di planet ini. Manusia adalah hewan sosial, tapi kita punya cacat fatal: kita merasa lebih dekat ke yang paling mirip dengan kita.
Apa yang membuat manusia menjadi lebih baik dan lebih ramah secara biologis disebabakan oleh hormon cinta yang dikenal sebagai oksitosin. Suatu zat kimia yang mengalir deras di otak saat seorang ibu melahirkan bayinya. Tapi, suatu penelitian di tahun 2010, mengungkap sisi gelapnya. Ternyata, efek oksitosin tampak terbatas untuk kelompok sendiri. Hormon itu bukan hanya menaikkan rasa suka terhadap teman, tapi juga bisa memeperkuat rasa tak suka terhadap pihak tak dikenal. Hormon oksitosin tidak mendorong persaudaraan universal, justru memperkuat rasa “kelompok saya duluan”
Sebuah penelitian mengungkap bagaimana seseorang dapat berlaku kejam terhadap orang lain hanya karena mematuhi suatu perintah. Temuan ini bukan yang pertama setelah di tahun 1960, Stanley Milgram, seorang profesor psikologi mencari tahu sampai sejauh mana orang-orang akan mematuhi figur otoritas ketika disuruh untuk melakukan hal yang berlawanan dengan hati nurani dan membahayakan.
Namun, penelitian yang diterbitkan di jurnal NeuroImage ini, lebih jauh mengamati terkait aktivitas dari daerah otak tertentu selama tindakan kekejaman dan eksekusi berlangsung. Ketika seseorang mematuhi suatu perintah, maka otak yang terkait dengan empati dan rasa bersalah menjadi kurang aktif. Bagian otak yang mampu menggambarkan rasa sakit dan penderitaan orang lain pada diri kita sendiri. Dengan kata lain, seseorang akan menjadi kurang berempati ketika mematuhi suatu perintah. Ini mungkin menjelaskan mengapa orang dapat melakukan tindakan amoral di bawah paksaan.
Dinukil dan disarikan dari Humankind karya Rutger Bregman