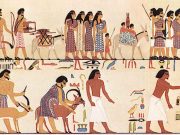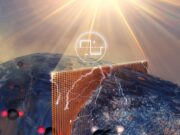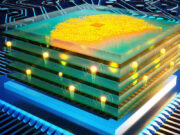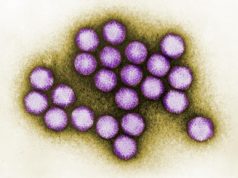Akhir Januari lalu, saat kasus positif COVID-19 belum dinyatakan terdeteksi di Indonesia sementara kasus infeksi pertama telah diumumkan di Singapura, Malaysia, Thailand, dan Australia, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memberikan tips berpikir positif untuk menghindari terkena infeksi coronavirus.
Kini, saat bencana penyakit ini memasuki bulan kedua setelah kasus pertama diumumkan, beberapa pakar kesehatan mental juga menganjurkan masyarakat agar berpikir positif sebagai strategi mengatasi masalah kesehatan mental di tengah ketidakpastian dan kecemasan yang tinggi akibat pandemi COVID-19.
Para penganjur itu bahkan mengklaim bahwa pikiran positif akan meningkatkan daya tahan tubuh sampai menangkal virus.
Dari kaca mata psikologi dan sejumlah riset, anjuran ini kurang spesifik, tidak sepenuhnya benar, dan bahkan membahayakan nyawa banyak orang, khususnya dalam situasi pandemi yang kesuksesan intervensinya sangat bergantung pada perubahan perilaku manusia secara massal, bersamaan, dan terkoordinasi.
Optimisme yang tidak realistis
Meskipun sudah ada penurunan aktivitas, berbagai laporan menyebutkan masih banyak warga yang belum sepenuhnya mengikuti anjuran menjaga jarak fisik antarorang, 1-2 meter di luar rumah, sebagai upaya memutus rantai penularan penyakit infeksi coronavirus.
Di Jakarta, misalnya, meskipun sudah ada penurunan jumlah penumpang kereta komuter (KRL) sampai 70 persen, arus lalu-lintas manusia dari kawasan Jabodetabek ke daerah-daerah lain di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur meningkat drastis. Para pemudik ini berpotensi menyebarkan virus lebih jauh ke daerah-daerah dan desa-desa yang sistem pelayanan kesehatannya lebih rapuh dibanding Jakarta.
Pola-pola ketidakpatuhan pada anjuran ahli kesehatan juga banyak ditemui di daerah lain.
Anjuran berpikir positif dengan harapan agar meningkatkan sistem kekebalan tubuh justru berisiko menimbulkan bias optimisme yang berperan besar memunculkan ketidakpatuhan ini.
Bias optimisme mewujud dalam tiga bentuk, yaitu:
(1) Ilusi kontrol, yaitu keyakinan berlebihan dapat mengendalikan situasi eksternal;
(2) Ilusi superioritas, yaitu keyakinan bahwa seseorang memiliki kelebihan daripada orang kebanyakan,
(3) Ilusi kemungkinan, yaitu ketika seseorang merasa kecil kemungkinannya dirinya akan mengalami hal negatif–dalam konteks ini yaitu, tertular atau menularkan penyakit.
Bias yang sama akan sangat berbahaya jika dialami oleh pengambil kebijakan, karena akan makin membuat rumit kondisi–bukan hanya di birokrasi pemerintah dan layanan fasilitas kesehatan tapi juga di masyarakat.
Bayangkan seorang presiden, para politikus di sekitar presiden, dan menteri kesehatan dari satu negara mengidap bias optimisme saat menghadapi pandemi. Padahal, mereka pengambil keputusan besar dan penting yang akan mempengaruhi hidup dan matinya puluhan hingga ratusan juta warga negara yang terserang wabah penyakit menular yang ganas seperti COVID-19.
Kementerian Kesehatan, misalnya, dikritik gagap, lamban, dan tidak transparan dalam menangani pandemi coronavirus karena ditengarai terlalu percaya diri setelah Indonesia berhasil mengendalikan wabah flu burung (H5N1) sejak 2003, SARS pada 2003, dan MERS pada 2012. Namun yang tak banyak diketahui, dalam kasus flu burung, korban meninggal terbanyak justru ditemui di Indonesia.
Bias optimisme ini mungkin juga membuat para pengambil kebijakan cenderung mengabaikan peringatan dari para ilmuwan.
Faktanya, sesuai dengan peringatan para ahli, virus SARS-CoV-19 menyebar sangat cepat dan mengikuti pola pertumbuhan eksponensial, meskipun sebenarnya dapat dicegah kemungkinan terburuknya jika diintervensi sejak dini.
Ekspektasi awam mengenai risiko tertular atau menularkan sangat mungkin tidak realistis, utamanya pada individu dengan literasi numerik yang kurang memadai karena kesulitan memahami logika eksponensial.
Anjuran “berpikir positif” itu kontradiktif dalam konteks mengendalikan pandemi karena memberikan rasa aman yang palsu, lebih-lebih ketika “berpikir positif” menjadi pesan utama anjuran di ruang publik.
Bertindak rasional
Anggapan bahwa berpikir positif dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh sebenarnya tidak sepenuhnya benar.
Riset yang dilakukan di Amerika Serikat dalam setting observasi natural dan percobaan di laboratorium menunjukkan bukti bahwa hubungan positif antara berpikir positif dengan kekebalan tubuh tergantung karakteristik sumber stres yang dihadapi. Ketika menghadapi ancaman yang ringan (langsung, singkat, dan mudah dikontrol), optimisme memang memberikan efek positif pada kekebalan seluler.
Namun bila yang dihadapi adalah ancaman yang lebih serius (kompleks, persisten, dan tak bisa dikontrol) maka yang terjadi justru sebaliknya.
Mengapa ini bisa terjadi? Dalam situasi sulit, optimisme justru menurunkan motivasi untuk mengambil tindakan mengakhiri atau menghindari sumber stres. Akibatnya, kemampuan sistem kekebalan tubuh justru malah menurun, bukan meningkat.
Hasil riset awal dari penelitian yang belum ditinjau sejawat menunjukkan bahwa responden yang merasa dirinya sangat mungkin tertular atau menularkan COVID-19 menunjukkan kecenderungan yang lebih besar dalam melakukan tindakan pencegahan, seperti mencuci tangan lebih sering dan menjaga jarak fisik dengan orang lain. Riset yang terbit akhir Maret lalu dilakukan di Amerika Serikat, melibatkan 1591 responden, dan dilakukan oleh peneliti California Institute of Technology dan University College London.
Meskipun sebagian besar responden menerka risiko mereka tertular COVID-19 cenderung menengah (rata-rata 43,56 dari rentang skor 0-100), namun terlihat ada perbedaan yang jelas ketika responden diminta menerka risiko umumnya orang Amerika Serikat tertular COVID-19. Secara umum, partisipan mengira risiko mereka tertular lebih rendah daripada orang Amerika Serikat pada umumnya, menunjukkan indikasi terjadinya bias optimisme.
Stop anjuran berpikiran positif
Riset-riset perilaku pada kasus epidemi sebelumnya, misalnya wabah flu babi (H1N1) di Italia dan Belanda, serta flu burung (H5N1) di Inggris, menyediakan bukti bahwa responden dengan persepsi risiko yang lebih tinggi akan lebih patuh pada anjuran ahli untuk melakukan tindakan pencegahan.
Yang paling menarik, sebuah riset pemodelan matematika pada 2012 dengan pendekatan game theory dalam memperkirakan efek respons manusia pada masa awal wabah influenza, menyebutkan bahwa ketika pada awal wabah masyarakat menerka risiko transmisi lebih besar daripada yang sesungguhnya justru malah berguna dalam melambatkan laju penularan. Perkiraan yang lebih buruk mengenai risiko tertular dan menularkan, sangat cepat dalam mendorong perubahan perilaku, utamanya dalam menurunkan frekuensi kontak sosial.
Singkatnya, merasa cemas dan terancam ketika pandemi adalah sesuatu yang normal, realistis, rasional, dan akan berpotensi menyelamatkan banyak nyawa.
Oleh karena itu, anjuran yang mempererat solidaritas sosial, kepatuhan pada anjuran ahli, dan peningkatan kewaspadaan lebih relevan daripada “berpikir positif” dan harus menjadi pesan utama yang ditonjolkan dalam imbauan kepada masyarakat.
Kejelasan aturan dan konsistensi kebijakan juga sangat besar dampaknya dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah sehingga respons terhadap wabah akan terkoordinasi dengan baik.
Meskipun tentu saja, ada potensi peningkatan kejadian masalah kesehatan mental.
Di Singapura, misalnya, dilaporkan bahwa saat ini klinik-klinik yang menyediakan layanan kesehatan mental dikunjungi lebih banyak pasien dengan keluhan stres dan kecemasan ekstrem dibanding kondisi normal.
Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa ada peningkatan kasus gangguan penyalahgunaan zat akibat kehilangan pekerjaan dan kerugian finansial. Masalah-masalah ini sesungguhnya lebih tepat diatasi secara kasuistik oleh tenaga kesehatan mental, dan upaya pemulihannya dapat dikerahkan ketika pandemi berakhir.
Pada masa awal pandemi seperti ini, hendaknya anjuran “berpikir positif” berhenti digaungkan. Saat seluruh upaya diarahkan untuk mendorong masyarakat waspada dan patuh pada anjuran ahli kesehatan, saran ini mudah sekali disalahpahami orang awam dan akibatnya dapat mengaburkan usaha perlambatan laju penularan penyakit.
![]()
Rizqy Amelia Zein, Assistant Professor in Social and Personality Psychology, Universitas Airlangga
Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.